Sebagian dari kalian yang sudah memasuki dunia profesional mungkin pernah mendengar, atau bahkan familier dengan istilah ini: native advertising.
Untuk sebagian lain yang masih menjalani pendidikan bidang komunikasi, rasanya kecil sekali kemungkinan kalian mengenal istilah tadi; kalaupun ternyata pernah tahu, ya bagus.
Tapi, apa sih native advertising itu?
Menjawab pertanyaan ini ya gampang-gampang susah, karena memang belum ada definisi yang berlaku resmi dan menyeluruh tentang istilah tersebut; hingga setiap praktisi bisa memiliki pengertian yang berbeda tentang iklan native ini.
Maka itu untuk saat ini, ada istilah lain yang bisa jadi mempermudah kita untuk memahami dan mewakili pola komunikasi pemasaran yang bisa dibilang sedang ngetren ini, yaitu: advertorial.
Kalau advertorial mungkin lebih banyak yang sudah memahami atau sekadar tahu, ya. Jadi sebelum lebih jauh membahas native advertising, mari kita ingat lagi dulu, apa itu advertorial?
Advertorial
Menurut buku Public Relations Writing (Iriantara, Yosal dan Surachman, A. Yani, 2006), advertorial merupakan bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. Istilahnya sendiri merupakan bauran dari kata “advertising” dan “editorial”.
Dalam penjelasan tambahan tentang advertorial pada buku ini, salah satu sifat utamanya adalah penampilan iklan mesti serupa dengan materi editorial lain pada sebuah penerbitan atau saluran media; dan isinya pun mesti dikemas sedemikian rupa agar juga bermanfaat untuk pembaca, seperti konten lain di media terkait.

Perhatikan kaus yang dikenakan Nirina Zubir. Dan menurut ulasan di sini, saat itu Darius Sinathrya (profil lain di rubrik ini) juga sedang menjadi brand ambassador produk yang tampil di kaus Nirina; dan tidak satupun dari dua artikel tentang Nirina pun Darius membahas tentang produk terkait.
“Fungsi utama advertorial bisa untuk jadi pendamping sebuah program komersial, menerjemahkan nilai komersial, atau menafsirkan kampanye komersial ke dalam format yang menarik audiens media yang dijadikan tempat beriklan,” seperti dikutip dari Public Relations Writing.
Pemahaman lain dari ilmuwan komunikasi Alo Liliweri, advertorial adalah bentuk iklan yang dikemas dengan teknik penyampaian pesan tertentu, hingga menyerupai sebuah berita atau tulisan khas (feature) pada media massa.
Sementara Philip Kotler menyebut periklanan secara umum terbagi menjadi iklan strategis dan taktis; advertorial tergolong ke dalam kategori strategis, karena fokusnya adalah mengkomunikasikan nilai brandsecara umum, sampai ke manfaat langsung dari produk atau jasa yang ditawarkan; dengan tujuan membangun relasi di antara konsumen dengan brand.
Pada Kleppner’s Advertising Procedure, advertorial merupakan pilihan untuk brand menawarkan pandangannya terhadap hal tertentu dalam bentuk iklan (konten berbayar).
Advertorial sendiri sudah diterapkan sejak lama di berbagai media massa di Indonesia, mulai dari koran, tabloid, majalah, radio, sampai televisi. Kita bisa melihatnya di media cetak, pada halaman yang memiliki label “Advertorial” atau “Inforial”.

Native Advertising
Sekarang mari kita coba kembali lagi ke native advertising, menurut praktisi pemasaran Joe Pulizzi ada 3 (tiga) hal utama terkait istilah itu:
- Berbayar. Ya, namanya juga iklan, jadi brand atau pengelola produk atau jasa mesti membayar placement di media terkait. Kalau tidak bayar maka tidak bisa disebut native advertising.
- Dikemas dengan format konten khas media terkait. Kontennya mesti memiliki nilai guna dan daya tarik serupa dengan konten lain di media atau layanan yang dijadikan tempat beriklan.
- In-stream. Pengertian sederhananya, disajikan serupa dengan konten pada media atau layanan tertentu; karena salah satu tujuan utama native advertising adalah tidak mengganggu pengalaman audiens atau pengguna saat mereka mengonsumsi konten di media atau layanan tertentu.
Kalau ingin tahu uraian yang agak lebih kompleks, bisa coba cek Native Advertising Playbook dari Interactive Advertising Bureau (IAB) di tautan ini.
Inti dari uraian IAB di atas, dengan makin beragamnya bentuk media dan layanan informasi yang ditawarkan pada publik, maka iklan nativeberdasarkan medium yang digunakan pun bisa bermacam-macam; mulai dari iklan yang kita temukan di Google saat mencari kata atau frasa kunci tertentu, promoted tweets di Twitter, iklan di feed Facebook kita, sampai tentunya artikel berbayar di situs yang suka kita kunjungi.
Menurut Joe Pulizzi lagi, native advertising yang baik mesti menampilkan label atau keterangan bahwa konten tersebut adalah materi berbayar. Caranya bisa dengan menyematkan titel “Sponsored”, “Promoted”, atau “Advertorial”.
Ciri lain dari native advertising yang oke menurut Pulizzi adalah “nggak jualan” atau fokus pada informasi yang berguna untuk pembaca media bersangkutan. Tak hanya itu, konten juga mesti disajikan dengan karakteristik atau tone of voice yang selaras dengan materi lain di dalam media terkait.
Lalu, apakah ciri “nggak jualan” ini kemudian membedakan native advertisingdari advertorial? Nggak juga, karena soal itu sangat bergantung pada kesepakatan di antara pemasang dan pemuat iklan, yang biasanya tertuang dalam dokumen bernama brief.
Misal, dulu saat bekerja di redaksi majalah, saya pernah menggarap advertorial 4 (empat) halaman di majalah untuk tiga edisi berurutan tentang salah satu merek mobil; dan saat itu, alih-alih mempromosikan varian produk, pengelola merek lebih ingin menyajikan ulasan mendalam tentang keselamatan berkendara yang penting diketahui banyak orang; dan tanpa satu kalipun menyebut merek si pemasang iklan.
Model konten semacam itu sudah lazim betul di dunia produksi majalah. Misalnya lagi (untuk contoh yang menyebut nama produk), kalau pernah melihat etalase produk di sebuah majalah, katakanlah rubrik yang menampilkan kategori produk tertentu, contohnya jam tangan; biasanya, rubrik itu pun termasuk ruang iklan yang bisa dijual.
Jadi, dalam konteks editorial, sementara ini saya mesti bilang kalau native advertising sama dengan advertorial; sederhananya karena istilah “native” saya anggap sama dengan pengemasan advertising ke dalam bentuk editorial.
Justru saya merasa, istilah native advertising (berdasarkan medium yang digunakan) kurang pas untuk media sosial seperti Twitter atau Facebook, bahkan mesin pencari seperti Google; karena kontennya tidak dikelola oleh unit editorial, melainkan kontribusi publik atau hasil kerja mesin. Intinya, bagaimana mungkin kolektivitas publik atau mesin bisa menghasilkan konten yang native?
Maksudnya begini, menurut saya, konten baru bisa dibilang native kalau tersaji tak hanya dalam format sama dengan konten lain di sebuah saluran, tapi juga memiliki gaya, konteks, atau tone of voice serupa dengan konten yang biasa dikonsumsi audiens saluran terkait. Dan hal itu baru mungkin terjadi kalau arus konten yang biasa dikonsumsi audiens bisa dikontrol, misalkan oleh unit editorial (yang menentukan editorial style juga editorial policy).
Contoh, teman saya di majalah Cosmopolitan biasa menulis kemaluan perempuan dengan istilah Miss Cheerful, dan Mr. Happy untuk kemaluan lelaki. Saat ia menerima pesanan advertorial, ia pun menerjemahkan pesan iklan ke dalam kebijakan redaksional majalah Cosmopolitan, dan menggunakan istilah Miss Cheerful dan Mr. Happy tadi (tentunya sesuai kebutuhan si pemasang iklan) ke dalam naskah advertorial (lengkap dengan gaya penceritaan khas majalah Cosmopolitan). Menurut saya, ini native.
Hal semacam itu yang menurut saya tak akan pernah tercapai di media sosial sebagai medium (social media advertising seperti Promoted Tweet atau Facebook Ad), apalagi hasil kerja mesin seperti search engine atau misalnya, rekomendasi konten otomatis dari media B saat kita membaca konten di media A.
Untuk media sosial, salah satu cara bermain konten native yang saya anggap oke adalah melalui influencer atau akun berpengaruh; karena pesan iklan bisa disampaikan berdasarkan “editorial style” dari persona yang dipilih, sehingga pengikutnya merasakan kalau pesan iklan itu adalah ungkapan pribadi dari si influencer.

Jadi, kata kuncinya adalah publisher; baik native advertising atau advertorial, kontennya mesti dibuat oleh publisher, yang bisa berbentuk perusahaan media massa, sampai ke perorangan (blogger atau social media influencer). Maka, kalau ada brand yang aktif di media sosial lewat akun brand terkait, menurut saya itu sih bukan native advertising, meski format dan penampakannya sama dengan konten lain di layanan terkait.
Intinya, menampilkan konten serupa secara visual dan tata letak saja tidak tepat untuk disebut native advertising. Lagipula, bayangkan saja berapa banyak orang akan protes kalau tiba-tiba banyak banner bermunculan di tengah feed Facebook atau linimasa Twitter. Sementara kalau mereka tidak mendulang pemasukan dari iklan, dari mana uang masuk untuk memutar roda bisnis?
Maka pilihan terbaik untuk mereka adalah menampilkan iklan dalam wujud konten yang serupa dengan konten bikinan penggunanya.

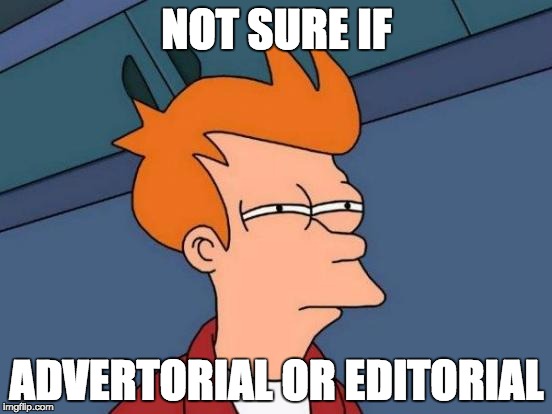









0 komentar:
Posting Komentar